Uji pra-klinis selalu melibatkan hewan untuk mengetes reaksi yang ditimbulkan bahan suatu produk. Ketika produk skincare nge-skip tahap ini, gimana konsumen bisa yakin kalau produk ini aman?
Pandemi COVID-19 bikin kita jadi punya hobi-hobi baru. Setidaknya dari curhatan orang sekitar, pengalaman pribadi juga sih, dan yang sering gue baca seliweran di timeline medsos, kebanyakan di rumah memang “maksa” orang-orang mencari cara untuk menyibukkan diri. Mulai dari berkebun, bersepeda, bikin kopi dalgona, marathon drama Korea, melihara ikan cupang, merajut, sampai nyobain resep-resep masakan. Sederetan hobi ini banyak yang dimulai lewat postingan satu orang di medsos, dengan konsep challenge maupun tutorial, terus diikutin beberapa orang lainnya, sampai kemudian viral dan menjadi tren.
Menurut peneliti medis yang dikutip Fast Company, punya hobi berdampak sangat baik untuk kesehatan fisik dan mental, apalagi ketika hobi itu membuat kita berinteraksi dengan orang lain. Meskipun jejaring tersebut dibangun secara virtual, kita tetap membutuhkan suatu ikatan khususnya ketika menghadapi dunia yang asing buat kita saat ini.
Masuk akal banget ketika misalnya, saling berbagi tips skincare sama mutualan di medsos bisa mengalirkan energi positif. Apalagi tren pemakaian produk skincare memang makin menjamur selama pandemi. Menurut laporan Statista pada September 2020, pengguna skincare di Indonesia paling menaruh minat ke produk-produk berlabel “organic”, “cruelty-free” atau “not tested on animals”, dan “hypoallergenic”.

Produk skincare berlabel cruelty-free lumayan banyak ditemukan pada merek-merek lokal. Ini yang sebetulnya menarik banget. Label cruelty-free atau biasa juga ditulis sebagai not tested on animals, artinya produk tersebut gak diuji ke hewan. Biasanya, uji pra-klinis melibatkan hewan untuk mengetes reaksi yang ditimbulkan bahan baku suatu produk. Penelitian untuk obatan-obatan dan vaksin pasti menggunakan hewan, mencit misalnya–tikus putih yang matanya merah, ini wajib, gak boleh skip. Baru setelah itu lanjut ke uji coba terhadap manusia.
Nah, uji coba ke hewan itu kan sebenernya buat tahu keamanan produk. Gimana kalau ada produk skincare yang nge-skip tahap ini? Kita gak bisa membahas ini tanpa bicara soal People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), organisasi pembela hak hewan terbesar di dunia. PETA rutin berkampanye menolak kekejaman terhadap hewan, termasuk praktik penyiksaan hewan untuk uji coba produk skincare dan kosmetik.
“Animals don’t worry about wrinkles, and we shouldn’t poison and kill them for our night cream.” – PETA
Karena misi organisasinya, PETA juga menyediakan sertifikasi untuk label-label seperti “cruelty-free”, “not tested on animal/no animal testing”, dan “vegan”. PETA bertindak sebagai pihak yang memverifikasi kalau klaim-klaim tersebut benar adanya. Selain PETA, ada organisasi lain dengan misi serupa, seperti Vegan Action dan The Vegan Society.
Tapi sampai saat ini, belum ada definisi legal buat klaim-klaim tadi. Artinya, gak ada standar atau kriteria baku suatu produk bisa disebut “cruelty-free” atau “vegan”. Masing-masing organisasi punya tafsiran sendiri. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengatur penggunaan label-label ini, jadi bebas dipakai tanpa diverifikasi. Begitu juga dengan Food and Drug Administration atau FDA (BPOM-nya Amerika Serikat), menulis dalam situs resmi bahwa belum ada definisi yang sah secara hukum untuk klaim semacam “cruelty-free”.
Bukan berarti juga kalau klaim-klaim tersebut dibuat sengaja untuk mengecoh konsumen. Ada pengguna produk skincare yang memang sangat selektif terhadap kandungan produk, misal harus plant-based atau bebas unsur hewani. Penambahan label “vegan” bakal sangat membantu dia memilih produk yang sesuai. Konsumen seperti ini biasa datang dari komunitas pencinta hewan semacam PETA.
Preferensi mereka mungkin bikin lo mikir, “Ngapain sih repot-repot mikirin nasib hewan? Mereka kan bukan spesies kita?” Jawabannya bisa ditarik dari perspektif evolusi. Dalam ulasan Frans de Waal, profesor zoologi primata di Emory University, menulis dalam “The Evolution of Empathy”:
“Kapasitas (empati) ini kemungkinan berkembang karena membantu kelangsungan hidup nenek moyang kita dalam dua cara. Pertama, seperti setiap mamalia, kita perlu peka terhadap kebutuhan keturunan kita. Kedua, spesies kita bergantung pada kerja sama, yang berarti bahwa kita akan lebih baik jika dikelilingi oleh teman kelompok yang sehat dan cakap.” – Frans de Waal
Rasa empati antar-spesies yang berlainan, tapi berdekatan dalam taksonomi, berkembang dari kebutuhan dasar organisme untuk bertahan hidup. Dalam hal ini, manusia bisa merasakan emosinya terhubung dengan mamalia lain karena pola pengasuhan yang menjadi kesamaan mendasar. Bayi mamalia belum mampu berjalan dan makan sendiri saat baru lahir, sehingga butuh dirawat induknya. Sifat belas kasih ini terus berevolusi dalam genetik kita dan menjadi alasan mengapa ada orang yang sangat membela kesejahteraan hidup beberapa hewan, tapi tetap mengonsumsi hewan lain atau menggunakan produk fashion berunsur hewani.
Terus gimana pecinta hewan bisa menghindari produk skincare yang tidak berseberangan dengan prinsipnya? Berdasarkan penggunaannya pada sebagian besar merek skincare, ada definisi yang dianggap mewakili isi kandungan-kandungan produk berlabel cruelty-free, no animal testing, dan vegan. Berikut penjelasannya dirangkum dari situs PETA, FDA, dan Ethical Elephant.
Daftar Isi
Cruelty free/no animal testing/not tested on animal
Label cruelty free atau no animal testing atau not tested on animal berarti pemilik produk skincare tidak menguji produknya ke hewan, baik itu untuk bahan, formulasi, atau produk final. Perusahaan juga tidak membeli bahan, formulasi, atau produk apapun dari pemasok yang menguji ke hewan. Selain itu, perusahaan juga tidak membayar pihak ketiga untuk menguji produk ke hewan.
Akan tetapi, produk yang mencantumkan label ini mungkin saja tetap mengandung unsur hewani. Kecuali produsen menegaskan dengan memberi label “cruelty-free and vegan”.
Ada makna lainnya gak? Nah, mungkin aja perusahaan bisa mengeklaim produknya “cruelty-free” karena memang bukan dia yang menguji bahannya ke hewan, tapi peneliti terdahulu saat bahan itu pertama kali diperkenalkan. Misal, senyawa Zinc oxide udah pernah diuji ke hewan sebelumnya, karena itu data keamanan dan efikasinya udah tersedia. Senyawa ini yang biasa menjadi campuran lotion sunscreen atau tabir surya.
No animal ingredients/vegan
Label vegan dan no animal ingredients kerap digunakan bergantian untuk produk skincare yang tidak mengandung unsur hewani maupun turunannya, termasuk beeswax, karmin, lanolin, dan gliserin dari lemak hewan. Beeswax atau lilin lebah bersifat humektan atau mampu menjaga kelembaban, sehingga sering menjadi bahan campuran lipstik dan pelembab bibir. Sedangkan karmin berasal dari kutu daun yang biasa dipakai untuk pewarna merah alami. Lanolin berasal dari bulu domba dan berfungsi sebagai pelembab. Gliserin juga banyak terdapat di produk pelembab, hasil ekstrak dari lemak hewan.
Sama dengan produk berlabel cruelty-free, klaim vegan bukan berarti proses pembuatan produk tidak melibatkan uji coba ke hewan. Kecuali produsen mencantumkan label “cruelty-free and vegan”.
Tanpa diuji ke hewan, gimana menjamin keamanan produk?
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan produk cruelty-free, kalangan ilmuwan terus mengembangkan pengujian alternatif tanpa hewan. Mereka berpegangan pada prinsip 3R yang dicetuskan WMS Russel dan RL Burch pada tahun 1959:
1. Replacement (Penggantian)
Metode ini menghindari atau menggantikan penggunaan hewan dalam penelitian produk skincare, kosmetik, termasuk produk perawatan tubuh seperti sabun, shampo, dan sikat gigi.
2. Reduction (Pengurangan)
Metode ini meminimalkan penggunaan hewan namun tetap menghasilkan informasi dan data yang realible atau dapat diandalkan.
3. Refinement (Perbaikan)
Metode ini memandu peneliti untuk menjalankan prosedur yang mengurangi rasa sakit, stres, atau bahaya pada hewan dalam pengujian di laboratorium. Refinement menjadi jalan tengah saat penggunaan hewan tidak dapat dihindari.
Pendekatan 3R bertujuan untuk mengurangi (dan pada akhirnya menggantikan) tes hewan dalam evaluasi keamanan produk. Salah satu cara yang ditempuh sebagai alternatifnya adalah dengan memakai teknologi berbasis rekayasa jaringan atau tissue engineering.
Sebelum lanjut, ada dua poin penting untuk memahami bagaimana suatu produk bisa lolos uji keamanan, sebagaimana dikutip dari publikasi Cosmetic Advancement Committee of China Health Care Association terbitan Maret 2021.
(1) Eksposur/paparan suatu bahan
Peneliti harus mendata tingkat konsentrasi semua bahan dalam formulasi produk, jumlah konsentrasi aman per penggunaan, dan frekuensi penggunaannya. Kalian tiap nyobain produk skincare, selalu ngecek instruksi di kemasannya gak? Ini penting banget buat jadi panduan biar ngegunainnya gak sembarangan.
Misal, di petunjuk kemasan, produk cuma boleh dipakai dua kali dalam satu minggu. Nah, petunjuk itu udah berdasarkan tes eksposur yang dijalankan produsen. Batas pemakaian diperoleh dari hasil tes di mana dosis amannya maksimal cuma dua kali seminggu, lebih dari itu mungkin aja menimbulkan risiko iritasi kulit, alergi, atau kerusakan jaringan.
(2) Informasi bahaya toksikologi pada bahan-bahan dalam produk
Peneliti menguji efek berbahaya dari paparan suatu bahan terhadap kesehatan manusia. Dari tes ini, peneliti bisa memperoleh data terkait risiko penggunaan produk, antara lain iritasi, tingkat korosifitas (kerusakan) akibat reaksi kimia produk, potensi memicu kanker, dan efek toksik pada DNA.
Teknologi rekayasa jaringan atau dikenal juga sebagai in vitro mampu menggeser tes hewan untuk mendapatkan sebagian dari informasi-informasi tersebut. Contohnya, sejumlah perusahaan sudah mulai meninggalkan prosedur tes Draize yang diperkenalkan ilmuwan FDA pada 1944. Tes Draize dilakukan dengan menetesi zat uji ke mata atau kulit kelinci yang dalam keadaan sadar, alias tanpa dibius. Tujuannya untuk mencari adanya tanda-tanda iritasi seperti kemerahan, pembengkakan, serta pendarahan.
Sebagai gantinya, peneliti memakai model 3D kulit manusia. Model ini terbuat dari sel keratinosit (komponen utama epidermis) asli yang dikultur dalam laboratorium. Untuk mendapatkan kulit tiruan sangatlah mudah karena dijual secara bebas dengan beberapa merek seperti EpiSKin, SkinEthic, dan EpiDerm.
Sayangnya, metode in vitro punya keterbatasan. Hewan masih dibutuhkan untuk menguji dampak paparan senyawa ketika memasuki sistem sirkulasi darah, terlebih efeknya pada keseluruhan sistem organ. Masalah kompleks seperti risiko kanker; perubahan DNA (mutagenesis); hubungan antara durasi dan frekuensi paparan, dosis, dengan perubahan di organ dan sistem organ, masih membutuhkan tes di organisme hidup.
Karena itu, khusus untuk obat-obatan, masih perlu pengujian hewan. Sampai saat ini belum ada penggantinya. Pengujian alternatif non-hewan sementara ini berfokus pada lini produk kosmetik, skincare, dan produk perawatan diri lainnya.
Terus sebagai konsumen, apa yang bisa kita lakuin? Kita bisa berpegang pada sertifikasi BPOM untuk menjamin keamanan seluruh produk yang beredar di Indonesia. Pastikan produk pilihan lo udah berlabel BPOM. Tanpa label itu, mending jangan ambil risiko ya. Buat ngecek status registrasi BPOM tiap produk, cari aja langsung di situs resmi milik BPOM: https://cekbpom.pom.go.id/.
Baca Juga:
Vaksin COVID-19 Cuma Akal-akalan Pembuat Vaksin, Bener Gak Sih?
Kenapa Ada Orang Yang Tidak Bisa Ngomong R Alias Cadel?
Carl Gustav Jung: Arti Introvert dan Ekstrovert Menurut Pencetus Aslinya
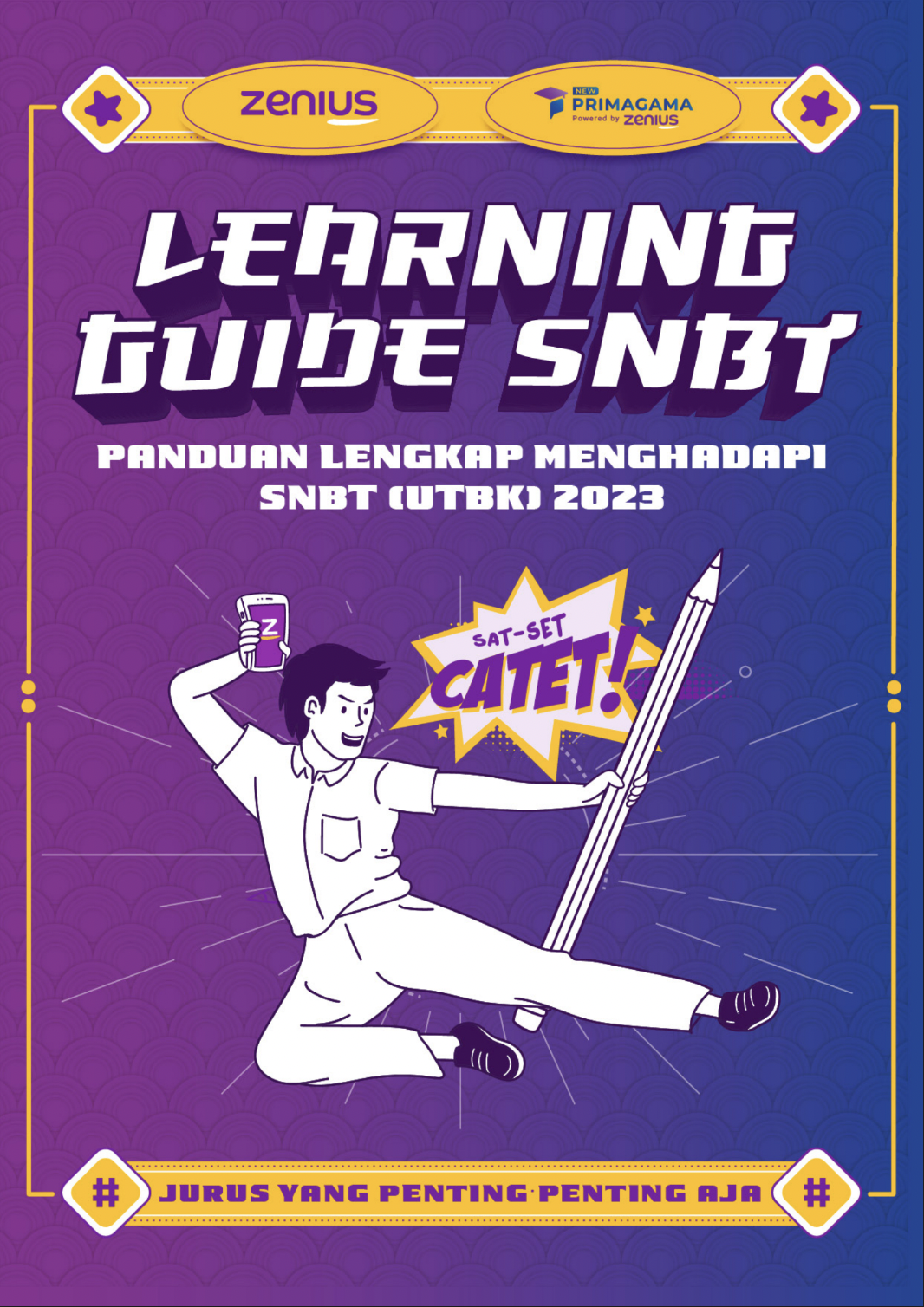









Leave a Comment